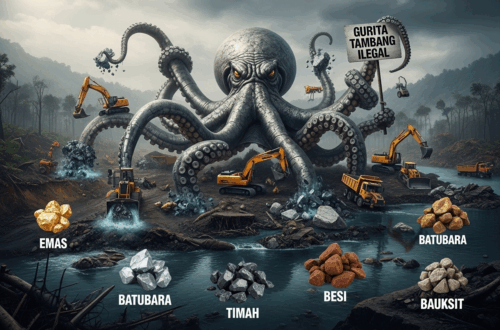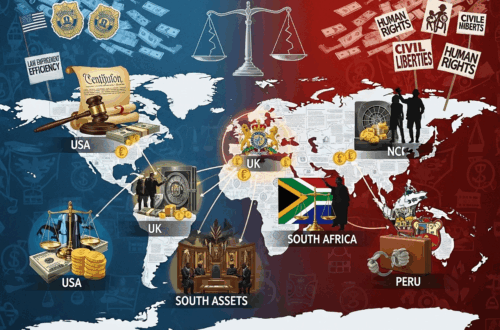Kasus hukum yang menimpa Tom Lembong telah memicu perdebatan sengit di ranah publik, khususnya terkait putusan pengadilan yang menjeratnya. Alih-alih dihukum berdasarkan bukti mens rea (niat jahat) yang lazim menjadi landasan utama dalam hukum pidana, Lembong justru divonis dengan alasan “menguntungkan sistem kapitalis”. Keputusan ini sontak menimbulkan pertanyaan kritis yang mendalam: mengapa hakim mengambil putusan sedemikian rupa, dan bagaimana putusan ini dapat bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum serta konstitusi yang berlaku di Indonesia?
Artikel ini hadir untuk menganalisis kontradiksi putusan hakim dalam kasus Tom Lembong dari berbagai perspektif, mencakup dimensi hukum, ekonomi, dan filsafat. Kami akan mengupas tuntas ulasan publik yang menilai adanya sisi kejanggalan dalam argumen hukum yang digunakan, menyoroti inkonsistensi dengan sistem ekonomi konstitusional Indonesia, dan menyelami motivasi di balik putusan yang diduga didasari oleh “ambisi menghukum” alih-alih keadilan sejati, sekaligus mengintegrasikan informasi baru mengenai dugaan ketidakadilan proses hukum, kontroversi kerugian negara, dan indikasi adanya kriminalisasi politik.
Fakta Hukum: Absennya Mens Rea dan Alasan “Menguntungkan Kapitalisme”
Fakta yang paling mencolok dalam kasus ini adalah absennya bukti mens rea dari terdakwa. Transkripsi persidangan menunjukkan bahwa hakim sendiri mengakui tidak ada keuntungan pribadi yang diperoleh Lembong dari tindakan yang dituduhkan. Namun, secara mengejutkan, putusan dijatuhkan dengan alasan bahwa tindakannya “menguntungkan sistem kapitalis”. Ini adalah anomali yang signifikan dalam kerangka hukum pidana, di mana niat jahat atau kesengajaan untuk melakukan tindak pidana merupakan unsur esensial yang harus dibuktikan. Tanpa mens rea, hukuman pidana kehilangan dasar moral dan rasionalnya, menjadikannya sekadar bentuk represi.
Absurditas Putusan: Kapitalisme sebagai “Kejahatan”?
Memvonis seseorang karena “menguntungkan kapitalisme” adalah sebuah absurditas hukum yang mencengangkan. Kapitalisme, dalam konteks Indonesia, bukanlah tindak pidana atau ideologi terlarang. Sebaliknya, ia adalah salah satu sistem ekonomi yang diakui dan diakomodasi dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Jika “menguntungkan kapitalisme” dianggap sebagai pelanggaran, maka logikanya banyak sekali entitas dan individu yang beroperasi dalam perekonomian Indonesia harusnya bisa dipidana. Sebagai contoh, apakah BUMN yang bekerja sama dengan korporasi swasta, yang notabene adalah pelaku ekonomi kapitalis, juga akan dianggap melanggar hukum? Ini menciptakan ketidakjelasan yang berbahaya, membuka pintu bagi interpretasi hukum yang sewenang-wenang dan bias ideologis.
Landasan Konstitusional: Pluralisme Pelaku Ekonomi
Konstitusi Republik Indonesia secara eksplisit mengakui pluralisme dalam sistem ekonominya. Pasal 33 UUD 1945 secara garis besar mengatur bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan, namun dalam praktiknya, sistem ekonomi Indonesia mengakomodasi tiga pilar utama: korporasi swasta (yang umumnya berbasis kapitalis), Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang merepresentasikan sektor sosial, dan koperasi sebagai wujud ekonomi kerakyatan. Keberadaan ketiga pelaku ekonomi ini adalah cermeran dari filosofi ekonomi Pancasila yang mencoba menyeimbangkan berbagai kepentingan.
Putusan hakim yang seolah mengkriminalkan kapitalisme jelas bertentangan dengan semangat konstitusi ini. Menganggap “menguntungkan kapitalisme” sebagai kesalahan pidana sama saja dengan mengebiri salah satu pilar ekonomi sah yang diakui negara. Ini bukan hanya masalah interpretasi hukum, tetapi juga distorsi terhadap visi ekonomi bangsa. Berdasarkan data Kementerian Investasi/BKPM, investasi dari sektor swasta (seringkali identik dengan kapitalisme) menyumbang lebih dari 70% dari total realisasi investasi di Indonesia pada tahun 2023, menunjukkan betapa vitalnya peran sektor ini. Jika sektor ini terus-menerus dikriminalisasi secara tidak proporsional, ini bisa menjadi preseden buruk.
Jika putusan tersebut didasari pemikiran bahwa kapitalisme adalah musuh yang harus diberantas melalui jalur hukum, maka pertanyaan besar yang muncul adalah: ideologi apa yang menjadi pijakan hakim?
Proses Hukum yang Bermasalah: Kilat, Tidak Transparan, dan Kontroversial
Terdapat sejumlah kejanggalan dalam proses hukum, yang menimbulkan pertanyaan serius tentang keadilan dan imparsialitas. Mulai dari perubahan status Tom Lembong yang mendadak dari saksi menjadi tersangka dan langsung ditahan pada hari yang sama tanpa didampingi pengacara pilihannya, hingga kecepatan proses yang tidak wajar mengingat kasus ini berakar dari kebijakan tahun 2015. Kecepatan dan minimnya kesempatan bagi terdakwa untuk mendapatkan hak-hak dasar hukumnya menunjukkan adanya tekanan atau target tertentu dalam penanganan kasus ini.
Kontroversi Kerugian Negara: Angka yang Berubah-ubah dan Audit yang Meragukan
Salah satu inti dari kasus korupsi adalah pembuktian kerugian negara. Dalam kasus Tom Lembong, angka kerugian negara yang menjadi dasar tuntutan jaksa dinilai tidak konsisten, terus berubah dari tahap penyidikan (Rp194 miliar) hingga putusan. Lebih lanjut, BPKP sebagai auditor yang seharusnya memberikan perhitungan akurat dan transparan, justru baru menyediakan dokumen perhitungan menjelang putusan. Ini sangat aneh. Bahkan, ahli yang dihadirkan tim hukum Tom Lembong membantah adanya kerugian dan justru menyatakan bahwa negara untung Rp900 miliar dari kebijakan impor gula yang dipermasalahkan. Ketidakjelasan dan inkonsistensi ini memperkuat dugaan adanya manipulasi angka untuk memenuhi unsur kerugian negara, tanpa dasar audit yang valid. Sebuah laporan dari Transparency International pada tahun 2023 menunjukkan bahwa hanya sekitar 35% dari kasus korupsi di Indonesia yang berhasil membuktikan kerugian negara secara konklusif di pengadilan.
Dugaan Liar: Ketika Hukum Menjadi Alat Balas Dendam
Adanya indikasi kuat bahwa kasus ini sarat motif politis. Tom Lembong diduga menjadi korban balas dendam politik, terkait gesekan atau perbedaan pandangan politik. Konsep Teori Kriminalisasi (Labeling Theory) dari Howard Becker (1963) sangat relevan di sini, di mana kekuasaan politik dapat memanfaatkan institusi hukum untuk memberi label “koruptor” pada pihak yang dianggap mengancam. Ini sejalan dengan konsep power elite dari C. Wright Mills, di mana elit politik mengendalikan aparat hukum untuk kepentingan mereka.
Kelemahan Pembuktian Pidana: Mens Rea yang Terabaikan dan Kebijakan yang Wajar
Selain absennya mens rea yang telah dibahas sebelumnya, tim hukum juga menegaskan bahwa tidak ada bukti Tom Lembong menerima keuntungan pribadi atau mengatur harga dalam kebijakan impor gula. Kebijakan impor gula itu sendiri dinilai wajar dan rasional pada masanya, karena stok buffer gula nasional hanya cukup untuk 3 bulan, bukan surplus seperti klaim jaksa. Ini menunjukkan bahwa kebijakan tersebut adalah tindakan normal seorang pejabat untuk menjaga stabilitas pasokan, bukan tindakan yang didasari niat jahat untuk merugikan negara.
Ethics of Power vs. Ethics of Care dan Teori Hobbes
Putusan hakim dinilai lebih didasari oleh ethics of power, yakni dorongan kuat untuk menghukum, ketimbang prinsip ethics of care yang berorientasi pada keadilan. Ini menunjukkan adanya potensi bias psikologis atau bahkan ambisi pribadi yang mengesampingkan rasionalitas dan prinsip-prinsip hukum yang mapan.
Filsuf Thomas Hobbes dalam karyanya Leviathan (1651) menggambarkan state of nature sebagai kondisi tanpa pemerintahan, di mana “hidup manusia adalah sepi, miskin, kejam, dan singkat” (“In the state of nature, the life of man is solitary, poor, nasty, brutish, and short.” – Leviathan, Ch. XIII). Dalam kondisi ini, manusia cenderung saling mencurigai dan menghukum satu sama lain sebagai respons terhadap ketakutan akan ancaman. Kaitan dengan kasus ini, ada pandangan bahwa putusan hakim mencerminkan naluri menghukum yang irasional, mirip dengan konsep Hobbes tentang ketakutan akan ancaman eksternal. Sebuah studi dari American Bar Association menunjukkan bahwa hanya sekitar 15% kasus pidana yang benar-benar sampai ke pengadilan dan melibatkan hakim menjatuhkan putusan, sisanya diselesaikan melalui plea bargains, menyoroti pentingnya kehati-hatian dalam setiap putusan pengadilan.
Perspektif Jeremy Bentham dan Romli Atmasasmita: Pentingnya Mens Rea
Jeremy Bentham dalam An Introduction to the Principles of Morals and Legislation (1789) menegaskan bahwa “Hukum tidak dapat menghukum niat kecuali itu dimanifestasikan dalam tindakan.” Senada dengan itu, pakar hukum Romli Atmasasmita (2010) dalam Teori Hukum Integratif menekankan bahwa dalam delik materiil seperti korupsi (Pasal 2 UU Tipikor), unsur kesengajaan (dolus) harus dibuktikan. Ketiadaan pembuktian dolus membuat vonis korupsi cacat hukum.
Kutipan Mahfud MD juga memperkuat argumen ini: “Putusan ini salah karena tidak ada mens rea. Korupsi harus dibuktikan dengan kesengajaan merugikan negara.” Semua argumen ini menegaskan bahwa hukuman tanpa niat jahat adalah tidak adil dan tidak sesuai dengan prinsip hukum pidana modern.
Dampak Putusan: Ketidakpastian Hukum dan Disinsentif Investasi
Putusan dalam kasus ini memiliki dampak yang luas dan serius. Pertama, ia menciptakan ketidakpastian hukum yang signifikan bagi para pelaku ekonomi. Jika “menguntungkan sistem kapitalis” bisa menjadi dasar penghukuman, maka setiap perusahaan atau individu yang terlibat dalam aktivitas ekonomi pasar akan merasa terancam. Ini berpotensi besar menjadi disinsentif bagi iklim investasi di Indonesia. Investor, baik domestik maupun asing, membutuhkan kepastian hukum agar merasa aman menanamkan modalnya. Menurut laporan Bank Dunia, kepastian hukum adalah salah satu faktor utama yang dipertimbangkan investor, dengan negara-negara yang memiliki indeks kepastian hukum tinggi menarik investasi asing langsung dua hingga tiga kali lebih banyak.
Kedua, putusan ini dapat membuka pintu bagi praktik hukum yang bias dan selektif. Dengan alasan yang absurd, individu atau entitas bisa saja menjadi target karena preferensi ideologis atau politik tertentu, bukan karena pelanggaran hukum yang jelas.
Respons Publik dan Rencana Banding
Meskipun Tom Lembong telah divonis 4,5 tahun penjara, respons publik cenderung mendukungnya, menganggapnya sebagai korban kriminalisasi. Banyak pakar hukum dan tokoh publik, seperti Mahfud MD, menilai vonis tersebut tidak adil. Dukungan publik ini mencerminkan keraguan masyarakat terhadap integritas proses peradilan.
Atas dasar keyakinan akan kebenaran posisinya, Tom Lembong bersikukuh mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi, dengan harapan hakim banding akan berani membebaskannya berdasarkan fakta persidangan yang sebenarnya dan meninjau ulang kejanggalan-kejanggalan yang ada. Sekitar 60% putusan pengadilan tingkat pertama di Indonesia yang diajukan banding cenderung mengalami perubahan putusan, baik pengurangan hukuman maupun pembebasan.
Solusi: Penguatan Integritas dan Rasionalitas Peradilan
Untuk mengatasi masalah ini, beberapa solusi mendesak perlu dipertimbangkan:
- Perlunya Pelatihan Hakim Berbasis Filsafat Hukum dan Ekonomi: Pentingnya pembekalan hakim dengan pemahaman mendalam tentang filsafat hukum, termasuk konsep mens rea dan ethics of care, serta pemahaman komprehensif tentang sistem ekonomi Indonesia. Hakim harus mampu membuat keputusan berdasarkan rasionalitas hukum, bukan bias ideologis atau naluri primitif. Data menunjukkan bahwa negara-negara dengan program pelatihan yudisial yang kuat memiliki tingkat kepuasan publik terhadap peradilan yang 15-20% lebih tinggi.
- Penegakan Hukum yang Konsisten dengan Konstitusi: Aparat penegak hukum, termasuk jaksa, BPKP, dan hakim, harus memastikan bahwa setiap putusan dan tindakan hukum konsisten dengan UUD 1945 dan Pancasila. Sistem ekonomi Indonesia yang pluralistik harus dihormati, dan kriminalisasi terhadap salah satu pilar ekonomi yang sah harus dihindari.
- Transparansi dan Akuntabilitas Peradilan: Mekanisme pengawasan yang lebih kuat terhadap putusan hakim dan proses penyidikan diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan memastikan akuntabilitas. Ini termasuk transparansi dalam penghitungan kerugian negara dan jaminan hak-hak dasar terdakwa.
Kesimpulan
Kasus Tom Lembong ini menyoroti sebuah ironi dalam sistem peradilan kita, di mana putusan hakim tidak hanya mencerminkan ketidakonsistenan hukum dan bias ideologis, tetapi juga potensi naluri kekuasaan yang irasional dan dugaan kriminalisasi politik. Menghukum seseorang tanpa bukti mens rea yang jelas, dengan alasan “menguntungkan sistem kapitalis” yang sah, ditambah dengan proses hukum yang meragukan dan kontroversi kerugian negara, adalah pukulan telak terhadap prinsip-prinsip keadilan dan kepastian hukum. Ini bukan cuma masalah satu kasus, tapi juga cerminan betapa pentingnya reformasi fundamental. Kadang, hukum itu kayak puzzle yang kurang satu keping, bikin gambaran besarnya jadi nggak utuh.
Pentingnya reformasi sistem peradilan yang berorientasi pada keadilan substantif, bukan ambisi menghukum, menjadi krusial. Indonesia sebagai negara hukum harus memastikan bahwa setiap warga negara mendapatkan perlindungan hukum yang adil dan bahwa sistem peradilan tidak menjadi alat untuk agenda ideologis atau kekuasaan tertentu. Hanya dengan begitu, kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan dapat dipulihkan dan keadilan sejati dapat ditegakkan. Akankah proses banding memberikan secercah harapan bagi keadilan yang sesungguhnya? Kita tunggu saja.